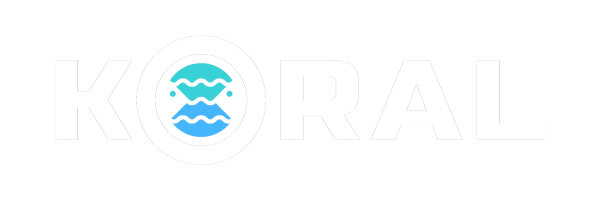Perubahan iklim global, polusi, hilangnya habitat, spesies invasif, dan penurunan tajam stok ikan laut, menimbulkan bahaya besar bagi lautan kita. Risiko terhadap laut ini begitu luas sehingga tidak ada area yang tersisa dan lebih dari 40% lautan telah terkena dampak serius. Akibatnya, umat manusia kehilangan akses persediaan dari lingkungan, makanan, dan pekerjaan penting yang disediakan oleh laut yang sehat.
Dampak perubahan iklim sekarang sudah dirasakan oleh nelayan. Karena ketergantungan kegiatan penangkapan ikan di laut mayoritas terletak pada cuaca, krisis iklim berdampak signifikan pada nelayan di banyak wilayah di Indonesia. Nelayan hanya bisa melaut selama 180 hari atau enam bulan per tahun jika cuaca di laut tidak mendukung. Hal ini dikarenakan tingginya gelombang di laut. Apalagi dampak perubahan iklim juga menyulitkan para nelayan untuk meramalkan cuaca. Jumlah nelayan yang meninggal di perairan Indonesia juga meningkat akibat isu iklim. Jumlah nelayan yang tewas di laut pada 2020, menurut WALHI, sebanyak 251 orang. Jumlah ini bertambah sejak 2010 yang hanya 86 orang.
WALHI mengungkapkan, ke depan, krisis iklim akan terus memperburuk kehidupan nelayan di Indonesia. Menurut laporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yang dirilis pada 28 Februari 2022, krisis iklim diperkirakan akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu dan memaksa ikan untuk meninggalkan daerah tropis, sehingga mengurangi pendapatan Indonesia dari penangkapan ikan sebesar 24%.
Komitmen dari Pemerintah untuk menghalau laju perubahan iklim tentunya sudah sering dinarasikan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada bulan April yang lalu, membeberkan strategi ekonomi biru yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kesehatan laut dalam rangka menahan laju perubahan iklim, serta mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelautan secara berkelanjutan (Website KKP, 2022). Seperti yang sudah diketahui khalayak, strategi ekonomi biru yang digadang-gadang KKP membagi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) jadi 6 zona penangkapan ikan dengan pertimbangan diantaranya karakteristik perairan, komoditas perikanan utama ataupun karakteristik sosial ekonomi. Selain itu, ekonomi biru dengan sistem zonasi juga dilengkapi dengan perizinan khusus berupa batasan waktu maksimal hingga 15 tahun kepada para pelaku usaha yang ingin memanfaatkan kuota tangkapan ikan. Zonasi Penangkapan Ikan Terukur nantinya akan membagi wilayah berdasarkan kategori sebagai berikut:
- Zona Penangkapan Ikan untuk Industri (Investor Dalam dan Luar Negeri) dengan kuota industri
- Zona Penangkapan Ikan untuk Nelayan Lokal (diutamakan tergabung dalam Koperasi) dan Investor Dalam Negeri
- Zona untuk Penangkapan Ikan Terbatas dan Spawning/ Nursery Ground

Regulasi dan Kebijakan Perikanan yang Berpihak pada Eksploitasi
Namun, apakah kebijakan ekonomi biru merupakan strategi yang tepat? KORAL pikir tidak. Strategi ekonomi biru dengan skema Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan skema zonasi merupakan salah satu wujud kebijakan ekstraktif. Pemberian perizinan dengan jumlah kuota sumberdaya ikan (SDI) yang dikonsesikan kepada industri-industri perikanan skala besar justru memperparah eksploitasi laut.
Bukan cuma itu, hanya adanya 1 Zona Spawning/ Nursery Ground yang didedikasikan untuk mengembangbiakan SDI juga menjadi bendera merah kebijakan ekstraktif. Itupun KKP juga tetap membuka ladang bagi penangkapan ‘intensif’ karena WPP 714 yang dijadikan zona Spawning/ Nursery ground ini juga didedikasikan untuk Zona Industri bagi investor Dalam dan Luar Negeri. Lalu bagaimana Pemerintah dapat menjamin ketersediaan SDI di masa depan, di zona-zona perikanan industri, apabila kemudian kegiatan pengembangbiakkan dan pelestarian hanya diadakan secara terbatas di satu zona saja.
Selain itu, kebijakan PIT masih belum memiliki kajian ilmiah tentang dampak yang akan ditimbulkan, dan juga bertentangan dengan asas keberlanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, yaitu asas keberlanjutan mengandung arti bahwa pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
Bukan hanya regulasi dan kebijakan yang mengatur sektor perikanan tangkap, tetapi juga wilayah konservasi hutan mangrove yang “katanya” menjadi agenda penting bagi Pemerintah namun masih belum jelas nasibnya. Bukan hanya upaya implementasi yang besifat occassional, Pemerintah Indonesia harus membuat regulasi khusus untuk melindungi keberadaan hutan mangrove. Apalagi mangrove bukan hanya berperan sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari ombak besar, tetapi juga merupakan suatu ekosistem penunjang untuk kelestarian dan kesehatan laut. Salah satu dampak dari minimnya mangrove di pesisir Indonesia bisa dilihat dari bencana banjir rob yang terjadi di Semarang, Demak, dan Pekalongan beberapa bulan yang lalu misalnya. Seiring berjalannya waktu, ancaman akan mangrove seperti proyek reklamasi dan pengalihan fungsi lahan menjadi pertambangan dan perkebunan juga semakin besar.
Sejauh ini mangrove memang sudah memiliki payung perlindungan, namun tidak ada satu regulasi yang benar-benar dibuat khusus untuk melindungi mangrove dan ekosistemnya. Selain itu, regulasi untuk mangrove masih “berceceran” dimana-mana. Saat ini saja terdapat delapan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pemanfaatan mangrove di Indonesia, baik di pusat maupun daerah mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Desa, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Sedangkan pada tingkat daerah ada gubernur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Tiap lembaga memiliki regulasi dan kebijakan masing-masing serta programnya sendiri-sendiri.
Laut yang dieksploitasi dengan adanya industri ekstraktif dan rendahnya kelestarian laut dan pesisir tentunya meningkatkan ancaman resiko perubahan iklim. Ibarat lingkaran setan, laut yang dieksploitasi akan memperparah ekosistem bawah laut seperti pemutihan terumbu karang dan punahnya padang lamun. Punahnya padang lamun dan tidak adanya terumbu karang sehat akan berpengaruh pada habitat plankton. Plankton sangat terkait dengan iklim dan kehidupan di Bumi. Plankton berfungsi untuk menyerap karbon. Fitoplankton menghasilkan gas yang disebut Dimetil Sulfida (DMS) yang merupakan partikel krusial dalam pembentukkan awan.
Kita adalah bagian dari lautan. Keberadaan bumi dan seisinya sangat bergantung pada laut yang sehat. Akan sangat ceroboh ketika kita justru membiarkan kerusakan terjadi, hanya karena ketamakan dan kepuasan yang dapat dirasakan jangka pendek.
******