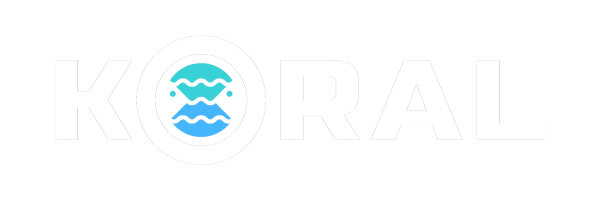Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.508 pulau (Kementerian Luar Negeri) yang dihuni oleh 360 suku bangsa. Tentunya manusia dan alam sudah hidup saling berdampingan sejak zaman nenek moyang kita dalam ruang hidup yang sama. Ekosistem pun bak rantai yang saling bertaut dan saling berdampak satu sama lain.
Berbicara mengenai ekosistem dan ruang hidup di wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tentunya masuk hitungan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, kriteria utama sebuah pulau dapat dikatakan sebagai pulau-pulau kecil adalah pulau berukuran lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Sementara ekosistem disini adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
Mengapa Pertambangan di Pulau Kecil Wajib Dilarang?
Kegiatan penambangan di pulau kecil mengancam kelestarian alam dan ruang hidup masyarakatnya. Mengapa demikian? Kegiatan pertambangan, termasuk didalamnya kegiatan eksplorasi, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan tambang dapat mengakibatkan perubahan penggunaan lahan, dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk penggundulan hutan, erosi, kontaminasi dan perubahan profil tanah, kontaminasi sungai, lahan basah setempat hingga wilayah pesisir dan laut, serta peningkatan kebisingan tingkat, debu dan emisi (Evidence Of The Impacts Of Metal Mining And The Effectiveness Of Mining Mitigation Measures On Social–Ecological Systems In Arctic And Boreal Regions: A Systematic Map Protocol, 2019).
Pengabaian tambang, decommissioning, dan penggunaan kembali tambang juga dapat mengakibatkan dampak lingkungan signifikan yang serupa, seperti kontaminasi tanah dan air. Selain tambang itu sendiri, infrastruktur yang dibangun untuk mendukung aktivitas pertambangan, seperti jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, dan jaringan listrik, dapat mempengaruhi jalur migrasi hewan dan meningkatkan fragmentasi habitat.
Bayangkan saja jika semua aktivitas tersebut dilakukan secara terus menerus di sebuah pulau kecil yang dihuni manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Sama saja seperti upaya ‘pembantaian’ tidak langsung dengan mematikan kelestarian lingkungan pelan-pelan. Bukan hanya ekosistem dan sumberdaya alamnya saja yang terbunuh, pertambangan di pulau-pulau kecil juga mengekspos resiko pada praktik tradisional masyarakat adat yang tinggal disekitarnya. Belum lagi konflik sosial misalnya seperti perampasan lahan yang seringkali menimbulkan peperangan antar warga yang pro dan kontra.
Pulau Kecil Semakin Terancam, Komitmen Pemerintah Cenderung Kerdil
Sudah banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang terancam bahaya kegiatan pertambangan. Pada tahun 2022, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan bahwa setidaknya ada 164 izin tambang di 55 pulau kecil di seluruh Indonesia. Pulau-pulau kecil ini termasuk Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara; Pulau Sangihe di Sulawesi Utara; Pulau Kodingareng di Sulawesi Selatan; Pulau Bunyu di Kalimantan Utara; dan Pulau Obi, Pulau Pakal, Pulau Gebe, dan Pulau Mabuli di Maluku Utara.
KORAL mengambil contoh kegiatan tambang nikel di Pulau Wawonii dan tambang emas di Pulau Sangihe. Kedua pulau ini menjadi korban pemerasan dan kerusakan kegiatan tambang akibat komitmen Pemerintah yang kerdil dan cenderung berpihak pada perusahaan tambang. Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara saat ini mengalami krisis lingkungan akibat tambang nikel.
Pulau dengan luas 867,58 km² ini dihuni oleh lebih kurang 37 ribu jiwa yang saat ini meronta mencari keadilan bagi pulau leluhurnya. Akibat pertambangan nikel yang diprakarsai PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan direstui Pemerintah, warga Pulau Wawonii harus kebanjiran sial (BACA: KABAR DARI PULAU KECIL YANG DITAMBANG: CERITA TENTANG KEADILAN DAN DEMOKRASI). Air tanah mereka tercemar dan berubah menjadi merah. Masyarakat telah dipaksa untuk membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk konsumsi, karena lumpur dari kegiatan pertambangan telah tercampur dengan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari menjadi warna coklat pekat. Belum lagi bencana banjir bandang yang menghampiri mereka setiap tahun semenjak proyek tambang itu berjalan.

Sementara nasib Pulau Sangihe juga tidak kalah tragis. Perjuangan warga Pulau Sangihe membebaskan pulau berukuran tak lebih dari 737 km² sangat berat dan panjang. Sejak tahun 2021, Pulau Sangihe sudah ‘dijajah’ tambang emas milik PT. Tambang Emas Sangihe (PT. TMS). sedikit demi sedikit sumber daya alam Pulau tersebut dikeruk walaupun konflik dengan masyarakat setempat terus terjadi. Kerusakan alamnya pun semakin hari kian parah. Hingga kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.Jkt tanggal 31 Agustus 2022 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 tanggal 12 Januari 2023 memutuskan bahwa kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BACA: LEBIH BERHARGA DARI EMAS: SANGIHE HARUS SELAMAT DARI TAMBANG!).

Namun komitmen Pemerintah rasanya cenderung kerdil. Salah seorang pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa PT. TMS dapat mengajukan kembali izin operasi produksi dengan melengkapi syarat-syarat tertentu. Jull Takaliuang, aktivis Save Sangihe Island atau Selamatkan Sangihe Ikekendage (SSI) mengatakan bahwa Kementerian ESDM melanggar hukum, jika memperlakukan Pulau Sangihe seolah-olah pulau tak berpenghuni. Hal ini terbukti ketika PT TMS diberi konsesi tambang emas seluas 42.000 hektar di sisi selatan Pulau Sangihe. Luas lahan tersebut sebesar 57% dari luasan Pulau Sangihe sendiri. Adapun konsesi tersebut diberikan sejak tahun 1997 sesuai dengan Kontrak Karya (KK). Selain itu, kurangnya komitmen Pemerintah untuk membela Pulau Sangihe juga nampak dari sikap pemerintah dan penegak hukum yang memungkinkan PT TMS terus beroperasi secara ilegal, meskipun secara tidak langsung. Jull menyatakan bahwa perusahaan tambang besar yang bermitra dengan CV Mahamu Hebat Sejahtera, perusahaan lokal, telah mengambil sebagian saham PT TMS.
Belum juga masalah di pulau-pulau kecil tersebut selesai, sudah bertambah pula satu pulau lagi yang terancam. Pulau Rempang di Batam saat ini tengah bergejolak. Sejak 7 September 2023, terjadi bentrokan antar warga setempat dengan aparat gabungan TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam. Hal ini dikarenakan warga menolak lahannya diambil alih untuk pembangunan lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Dilansir dari laman resmi WALHI, Zenzi Suhadi selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebut pembangunan kawasan Rempang Eco-City merupakan salah satu program strategis nasional yang dimuat dalam Permenko Ekuin Nomor 7 Tahun 2023. Program Strategis Nasional ini dari awal perencanaannya tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang sudah eksis sejak 1834. Jadi wajar masyarakat di lokasi tersebut menolak rencana pembangunan ini. BP Batam, Menko Ekuin, Kepala BKPM, dan K/L yang terlibat dalam proses ini merumuskan program tanpa persetujuan masyarakat.

Fakta-fakta diatas seolah membuktikan komitmen Pemerintah dan keberpihakannya akan warga pulau-pulau kecil dan keberlanjutan lingkungan perlu dipertanyakan. Apakah memang, Pemerintah setega itu melelang alam dan segala isinya demi keuntungan semata? Tidak sadarkah Pemerintah bahwa seberapa besarpun keuntungan tersebut, belum tentu dapat mengembalikan tanah leluhur yang rusak akibat kegiatan eksploitasi tambang? Ataukah Pemerintah sebegitu jumawa dan tega, melegalisasi aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, merampas hak atas ruang hidup yang layak, hak atas rasa aman, hak akses terhadap pangan, serta hak atas pekerjaan? KORAL berharap Pemerintah setidaknya punya cukup keberanian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
***