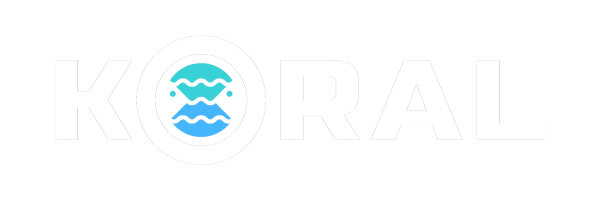Hari Tanpa Kekerasan Internasional merupakan salah satu hari penting yang dirayakan dunia pada bulan Oktober. Dilansir dari situs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), resolusi Majelis Umum A/RES/61/271 tanggal 15 Juni 2007 menetapkan peringatan Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Masih dari situs yang sama, prinsip non-kekerasan – juga dikenal sebagai perlawanan tanpa kekerasan – menolak penggunaan kekerasan fisik untuk mencapai perubahan sosial atau politik. Sering digambarkan sebagai “the politics of ordinary people” atau “politik rakyat biasa”, sebuah bentuk perjuangan sosial ini telah diadopsi oleh banyak orang di seluruh dunia dalam kampanye keadilan sosial.
Hal ini sedikit banyak mengingatkan kita akan perjuangan keadilan ruang hidup dan adat yang saat ini tengah terjadi di sebuah pulau kecil di Indonesia. Saat ini, mayoritas masyarakat Pulau Rempang tengah berjuang membebaskan tanah leluhur mereka dari penjajahan atas nama investasi. Dilansir dari BBC Indonesia, di Kampung Pasir Merah, Sembulang, terdapat posko bantuan hukum yang didirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Posko ini bak benteng pertahanan bagi masyarakat kampung tua Melayu yang menolak keras direlokasi.
Sebelumnya, terdapat rencana penggusuran sebelas Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang dan juga lima Kampung Melayu Tua di Pulau Galang dan Galang Baru. Penggusuran ini demi melenggangkan pembangunan pabrik kaca milik Perusahaan Xinyi Group di atas tanah adat seluas 2000 hektar (Walhi, 2023). Sedikit banyak penggusuran ini juga terkait dengan rencana pembangunan proyek Rempang Eco-City. Diketahui bahwa pembangunan kawasan investasi terpadu di Rempang akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Proyek bernama Rempang Eco City itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada 2080.
Dengan keberadaan wacana ini, masyarakat Pulau Rempang terancam hengkang dari tanah leluhur mereka. Demi mempertahankan tanah leluhur dan warisan sejarah didalamnya, warga pun menolak keras. Konflik pun tidak terhindarkan. Tepatnya di tanggal 7 September 2023, terjadi bentrokan antara aparat dan warga dalam proses pengosongan lahan secara paksa hingga menyebabkan jatuhnya korban. Dilansir dari Media Indonesia, bentrokan aparat dan warga dipicu penolakan warga Kampung Adat Masyarakat Melayu.
Kekerasan dan pemaksaan bukan hanya terjadi di tanggal 7 September saja. Menurut pengakuan warga kepada Ombudsman, pemaksaan dan tekanan dilakukan dengan berbagai cara. “Kalau nggak ada orang di rumah, form-nya dimasukkan ke bawah pintu. Kalau nggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah untuk mengisi form dan tanda tangan,” kata anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro.
Bukan Tanpa Penghuni, Pulau Rempang Kaya Akan Sejarah, Budaya, dan Ekosistemnya
Perlu diketahui oleh Sobat KORAL, bahwa Pulau Rempang bukan pulau tidak berpenghuni. Berdasarkan temuan Ombudsman, kampung-kampung tua di Pulau Rempang telah eksis sejak lama. Bahkan jejak-jejak sejarah seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), makam-makam tua, tapak tugu, patok tanda batas antar kampung, hingga dokumen Ijazah sudah ditemukan sejak tahun 1989.
Bukan hanya dokumentasi dan bukti legalitas yang tersedia, Pulau Rempang juga kaya akan nilai sejarah dan budaya. Dalam surat yang ditulis oleh Hj. Azlaini Agus, seorang tokoh adat asal Riau, kepada Menko Polhukam RI Prof. DR. H.M.Mahfud MD (Walhi Riau, 2023), Pulau Rempang menjadi saksi bisu pertahanan dan perlawanan para prajurit leluhur masyarakat Pulau Rempang, melawan penjajahan Belanda dan Inggris. Pada Perang Riau I (1782-84) dan Riau II (1784-87), para prajurit ini disebut sebagai Pasukan Pertikaman Kesultanan. Anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami pulau Rempang, Galang, dan Bulang secara turun temurun. Diketahui saat ini Pulau Rempang memiliki 16 kampung tua yang dihuni masyarakat adat dari berbagai suku. Setidaknya diketahui bahwa suku Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat telah tinggal di sana sejak tahun 1834. Sebagian besar dari mereka saat ini berprofesi sebagai nelayan dan pedagang.
Sumber daya alam di Pulau Rempang juga sangat kaya. Sebagaimana dirilis oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, keadaan ekosistemnya menjadi alasan dipilihnya Pulau sebesar kurang lebih 16.583 km² sebagai salah satu wilayah yang dilindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Sumber Daya alam di Pulau Rempang memiliki banyak potensi, termasuk flora, fauna, ekosistem, dan objek wisata.
Terbaru, nelayan tradisional di Pulau Rempang dan sekitarnya mulai buka suara. Penolakan dari nelayan baru muncul setelah dilaksanakan konsultasi publik Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh BP Batam pada 30 September 2023 lalu di Kantor Camat Galang, Pulau Rempang, Kota Batam (Tempo, 2023). Nelayan menolak adanya Rempang Eco-City karena kekhawatiran akan dampak buruk bagi laut dan pesisir. Bahkan dampaknya pun mulai terlihat dari kegiatan pembangunan pelabuhan bongkar muat di pesisir Kampung Pasir Merah, Sembulang, Pulau Rempang, yang menghadap langsung ke Pulau Mubut.
Dorman, selaku nelayan tradisional dari Pulau Mubut mengatakan, perairan lokasi mereka melaut tersebut dalamnya hanya sekitar lima meter. Jika akan dibangun pelabuhan, tentu akan ada pengerukan pasir dan reklamasi. “Otomatis dampaknya pasti kepada kondisi laut, karang rusak, ikan hilang, udang juga akan hilang,” ujarnya (Tempo, 2023). Padahal, karang itu menjadi tempat pemijahan biota laut. Ketika terumbu karang rusak, maka nelayan dan sumber penghasilan mereka akan terancam. Area konservasi yang berada dekat dengan Pulau Rempang pun dikhawatirkan akan terdampak. Kawasan konservasi tersebut berada tidak jauh dari pesisir Sembulang yang menjadi lokasi utama pembangunan Rempang Eco-city yang masih dihuni oleh sejumlah fauna terancam punah seperti dugong, penyu, hingga lumba-lumba.
Berlanjut di Part-2!
KORAL masih akan mengupas lebih dalam kisah perjuangan, keberadaan AMDAL, dan intrik lainnya dalam konflik Pulau Rempang di Part-2! Mau baca? Klik disini ya!
***