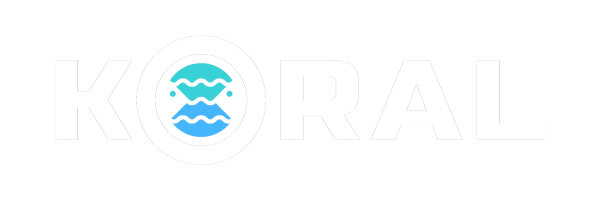Pada 6-18 November 2022 yang lalu, Sharm el Sheikh, Mesir, menjadi tuan rumah perhelatan para pemimpin negara. Tidak lain dan tidak bukan adalah acara Konferensi Anggota Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau Conference of Parties UNFCCC ke-27. Perhelatan COP27 kali ini dihadiri oleh sekitar 45 ribu orang dari segala golongan dan komunitas, termasuk para ilmuwan dan komunitas pemerhati lingkungan dan perubahan iklim, salah satunya anggota koalisi KORAL – WALHI.
UNFCCC sendiri merupakan badan PBB yang mengkurasi aturan dasar dan kerangka persatuan negara-negara dalam melawan perubahan iklim sejak tahun 1992. Per tahun ini, UNFCCC sudah memiliki 196 negara yang bergabung dalam lembaga yang menggelar COP di tiap tahunnya dan menghasilkan beberapa perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, Pakta Iklim Glasgow, dan juga ambil bagian dalam mendorong Indonesia untuk melarang pembangunan PLTU baru.
Namun sayangnya, COP27 dianggap tidak menghasilkan solusi apapun. Wadah yang diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata ini justru mandul kesepakatan dalam menangani isu-isu utama. Padahal ultimatum sudah dikeluarkan yaitu meningkatnya suhu bumi sebesar 1.5℃ per 2030. Hal ini akan mengancam bumi beserta isinya dalam perubahan iklim masif dan tinggi resiko destruktif.
Dihadiri Ratusan Pelobi Perusahaan Migas Dunia dan Solusi Rawan Hidden Agenda
Pada acara COP27, seruan untuk menghapus penggunaan bahan bakar fosil – sebagai sumber emisi gas rumah kaca; justru diihadang oleh negara-negara penghasil minyak, dan sebagian delegasi seperti tenang-tenang saja meski laju dekarbonisasi sangat lambat. Padahal apabila semua komitmen terkait pengurangan atau penghentian subsidi bahan bakar fosil dilakukan saja, ancaman kenaikan rerata temperatur masih berada di kisaran 2.7℃.
Hal ini juga dapat dilihat dari kehadiran 636 pelobi di COP27. Mereka adalah utusan dari perusahan minyak dan gas yang justru menginfiltrasi forum-forum COP27. Lucunya, jumlah kehadiran para lobbyist ini lebih banyak daripada delegasi negara anggota UNFCCC. Keberadaan mereka menjadi salah satu faktor utama kegagalan COP27.
Selain itu, dalam COP2 terdapat poin perdagangan karbon dan dicetuskanlah skema carbon offset yang dianggap sebagai penyeimbang karbon. Padahal skema tersebut bak “izin” yang diberikan untuk mencemari, merusak, dan melepas emisi dengan menjaga stok karbon di tempat lain (WALHI, 2022).
Nasib Masyarakat Pesisir dan Perairan Indonesia
Dilansir dari laporan The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) yang diterbitkan Food and Agriculture Organization (FOA) di tahun 2022, 90,3 juta ton ikan dihasilkan dari perikanan tangkap dan hanya 33.1 juta ton yang dihasilkan oleh perikanan budidaya. Laut juga menjadi entitas ekologis penyerap karbon terbesar dan penghasil oksigen terbesar dibandingkan hutan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa peran laut menjadi sangat penting bagi kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi ini.
Meskipun fakta di atas berkata demikian, ditambah sudah banyaknya peringatan ilmiah yang mengerikan, negara-negara Global Utara termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara-negara di Uni Eropa memiliki tanggung jawab historis terbesar atas emisi yang menyumbang faktor degradasi lingkungan. Hal ini merugikan banyak pihak termasuk didalamnya masyarakat pesisir dan juga wilayah perairan di negara-negara maju seperti Indonesia. Sementara, dalam COP27 yang diharapkan mampu menjadi wadah solusi bagi keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, justru malah mendukung geoengineering dan blue economy yang menambah “beban” laut. Kedua skema dan aktivitas ini justru menambah ancaman dan resiko kerusakan laut dengan eksploitasi dengan topeng ramah lingkungan.
Saat ini, tidak bisa dipungkiri dampak dari perubahan iklim yang semakin parah sudah terasa ditengah-tengah masyarakat pesisir. Misalnya dengan naiknya permukaan laut, cuaca ekstrim, kerusakan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, serta buruknya manajemen limbah dan sampah (mikroplastik) yang masih mengancam perairan Indonesia. Dampak yang sudah disebutkan tadi pun belum termasuk multiplier effect seperti erosi, banjir rob, hingga ke pengasaman air laut.
Dampak yang dirasakan Indonesia di kawasan pulau kecil dan pesisir yang paling dirasakan adalah hilangnya 1 hektar tanah di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah tiap tahunnya akibat meningkatnya permukaan air laut sejak tahun 1997. Pada masa yang akan datang, lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia akan terancam tenggelam akibat kenaikan air laut yang disebabkan oleh krisis iklim (BPS, 2021). Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, WALHI mencatat sebanyak 5.416 desa pesisir yang tenggelam karena banjir rob, di tahun 2050 sebanyak 199 kota atau kabupaten di pesisir Indonesia akan terkena banjir rob (WALHI, 2020). Kerugian ini akan dialami oleh 23 juta warga Indonesia dengan kerugian ekonomi sebesar Rp 1.56 triliun (Kompas, 2021).
Nelayan terutama adalah korban pertama yang akan paling terdampak. Kehilangan peluang kerja, hancurnya perekonomian mereka, hingga hilangnya nyawa nelayan di laut menjadi bukti kerusakan lingkungan. Setiap tahun, (rata-rata) 100 nelayan hilang dan meninggal di laut akibat melaut pada saat cuaca yang tidak menentu. Jumlah nelayan yang meninggal di laut pun terus meningkat. Di tahun 2010 jumlahnya tidak lebih dari 87 orang, sementara di tahun 2020 menjadi 251 orang (WALHI, 2020).
Selain itu, salah satu indikasi semakin turunnya kualitas laut akibat eksploitasi dan aktivitas destruktif di perairan adalah tingkat keasaman air laut. International Atomic Energy Agency (IAEA) mengatakan bahwa saat ini, tingkat keasaman air laut sudah naik 30% (yaitu pH 8.0-8.2) dibanding era pra-industrial dan akan menginjak angka pH 7.8 dan membuat laut menjadi 150% lebih asam dan akan menciderai setengah dari biodiversitas laut.
Harapan KORAL akan Partisipasi Indonesia
Indonesia masuk ke dalam top 50 negara di dunia yang paling terdampak dari perubahan iklim dan degradasi kualitas lingkungan sebagai salah satu negara maju yang sangat aktif mengekstraksi sumber daya alamnya. Berikut beberapa harapan KORAL akan partisipasi Indonesia.
Keberadaan Indonesia sebagai salah satu dari 3 negara aliansi hutan yang berhubungan erat dengan karbon diharapkan mampu menggunakan posisinya untuk mengutamakan hak rakyat atas wilayah yang mereka kelola termasuk di dalamnya hutan mangrove dan padang lamun. Apalagi menurut temuan WALHI, banyak wilayah kelola rakyat (WKR) yang berhasil melindungi hutan. Indonesia, Brazil dan Kongo juga diharapkan mampu menagih utang ekologis/ iklim kepada negara-negara maju bertanggung jawab secara mutlak atas kerusakan hutan dan meminimalkan konsumsi produk dari industri ekstraktif.
Selain itu, KORAL berharap, Pemerintah Indonesia mau berbesar hati untuk mengevaluasi, mencabut atau menghapus beberapa regulasi, kebijakan, dan program yang mengancam kelestarian wilayah pesisir dan perairan Indonesia. Diantaranya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, skema Ekonomi Biru yang mendorong Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Skema Zonasi dengan Perizinan Khusus. Jika wadah perhelatan internasional tidak bisa menjamin keberlanjutan biodiversitas dan kelestarian lingkungan, Pemerintah Indonesia harus mampu menggunakan hak sebagai negara berdaulat untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan negara kita demi masa depan generasi mendatang.
***