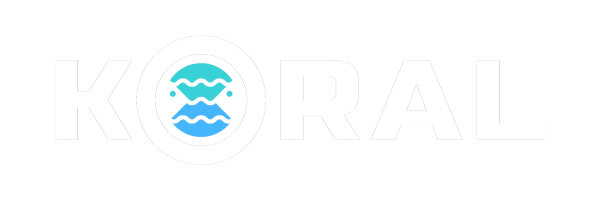Air merupakan kebutuhan pokok seluruh manusia. Air membentuk 60-75% dari berat tubuh manusia. Kehilangan hanya 4% dari total air tubuh menyebabkan dehidrasi, dan kehilangan 15% bisa berakibat fatal. Demikian pula, seseorang bisa bertahan sebulan tanpa makanan tetapi tidak akan bertahan 3 hari tanpa air. Bukan hanya secara biologis, manusia juga membutuhkan air untuk kegiatan mereka sehari-hari seperti memasak, mandi-cuci-kakus, dan lain sebagainya.
Sebegitu krusialnya peran air dalam kehidupan manusia, hak atas air (HA) telah diakui oleh undang-undang hak asasi manusia (HAM) internasional baik sebagai hak asasi manusia maupun “hak hukum”. HA pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak hukum atas air yang cukup, aman, terhormat, tersedia, layak, dan dengan harga terjangkau secara ekonomi. HA juga mencakup hak dan kebebasan untuk memelihara akses terhadap persediaan dan pengelolaan air, termasuk bebas dari gangguan akses air yang sewenang-wenang dan pencemaran.
Atas dasar inilah, privatisasi air menjadi masalah. Jika menurut Bakker, privatisasi air adalah “pengalihan kepemilikan sistem persediaan air ke perusahaan swasta, dan ‘kemitraan’ negara dan sektor swasta, baik pada pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan sistem pasokan air”. Alhasil, air menjadi barang komersial yang dapat diperjual-belikan demi keuntungan dan itu juga terjadi di Indonesia.
Sejarah Privatisasi Air di Ibukota
Privatisasi air pertama kali muncul di Ibukota. Jakarta menjadi saksi bisu dimulainya privatisasi air di Indonesia sebagai dampak dari “program penyesuaian struktural” pendanaan pinjaman Bank Dunia tahun 1990-an. Dengan mengintegrasikan sektor swasta, pemerintah Indonesia harus merestrukturisasi pengelolaan air dan pembuangan sampah. Selain itu, dua perusahaan internasional yang terkait dengan PDAM menyepakati Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk pengelolaan air di beberapa wilayah Ibukota untuk jangka waktu 25 tahun antara tahun 1997 dan 1998. Menyusul kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, jalan privatisasi menjadi semakin mudah diakses. Gagasan tentang “Hak Pemanfaatan untuk Perusahaan Air” diperkenalkan oleh undang-undang, dan hak ini dapat diberikan kepada sektor swasta dengan persyaratan yang lebih longgar untuk penggunaan komersial.
Pada 25 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 6 Juni 1997, PAM Jaya meneken kerja sama dengan PT Garuda Dipta Semesta bersama Lyonnaise des Saux (sekarang Palyja) dan dengan PT Kekarpola Airindo bersama Thames Water Overseas Ltd (sekarang Aetra). Selama seperempat abad itulah, PAM, Palyja, dan Aetra memegang kendali pelayanan air di Ibukota yang berujung pada intransparansi pengelolaan, pelayanan yang tidak merata, dan juga sarana prasarana yang tidak optimal.
Bukan hanya itu, harga air semakin melambung tinggi. Tercatat dalam penelitian yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2020 mengungkapkan, harga air meningkat 135% di rentang waktu 10 tahun pertama setelah adanya perjanjian kerja sama PDAM dan dua korporasi air di Jakarta.
Kerugian lainnya adalah carut marut keuangan negara yang menjadi collateral damage di masa depan. Dilansir dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), dalam kontrak privatisasi air Jakarta memang PAM Jaya selaku BUMD milik Pemerintah Provinsi harus menutup selisih tarif air masyarakat berpenghasilan rendah yang Rp1.050-Rp3.500 per meter kubik dengan harga air yang dipatok swasta yang sebesar kurang lebih Rp7.000 per meter kubik. Selisih ini harus bisa ditutup oleh PAM Jaya, dan jika tidak maka akan menjadi utang PAM Jaya. Alhasil yang ditakutkan adalah dengan semakin besar jumlah air yang disalurkan, utang PAM Jaya juga akan semakin besar dan merugikan keuangan negara.
Gugatan akan Privatisasi Air – Lebih Dari Sekadar Hak
Inilah yang kemudian mendasari gugatan masyarakat sipil ke Pemerintah dan pihak swasta terkait. KMMSAJ bersama dengan Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHa), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Solidaritas Perempuan dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggugat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, PAM Jaya, Palyja, dan Aetra, atas kelalaiannya memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia.
Hingga akhirnya pada tanggal 24 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Iim Nurohim, S.H memutuskan untuk mengabulkan gugatan warga sipil terkait privatisasi air Jakarta dengan menetapkan bahwa yang tergugat telah lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merugikan negara dan warga Jakarta. Dalam keputusan sidang itu juga disahkan pencabutan PKS antara PAM Jaya dengan pihak swasta terkait dan mengembalikan pengelolaan air minum ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Masa Depan Air di Ibukota – Jangan Ubah Jadi ‘Airmata’
Dengan adanya putusan hakim tersebut, resmilah pengakhiran kontrak PAM Jaya dengan dua pihak swasta sebelumnya. Namun babak baru telah dimulai. 14 Oktober 2022 yang lalu, PAM Jaya telah menandatangani kontrak dengan PT Moya Indonesia. Padahal, putusan Hakim terkait pemutusan PKS PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra belum diikuti dengan evaluasi dan laporan kinerja yang berarti. Hal ini membuat PAM Jaya seolah-olah menutup kerjasama lama dan siap mengulang kesalahan yang sama.
Ada beberapa alasan mengapa kemudian PAM Jaya dirasa tidak belajar banyak dari kesalahan sebelumnya. Menurut KMMSAJ, kerja sama PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia tidak secara spesifik menjelaskan mekanisme skema bundling penyelenggaraan air di Jakarta dan dapat memicu masalah baru di masyarakat. Lalu menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), tidak adanya transparansi antara kedua pihak kepada publik sebagai stakeholder yang paling terdampak, menimbulkan dugaan persekongkolan tender. Walaupun terlibat dalam sektor pengadaan pipa, seperti yang diutarakan Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin kepada Kompas (Februari, 2023), tetap saja transparansi menjadi salah satu faktor utama bagi masyarakat untuk dapat mengetahui kinerja Pemerintah, mengawasi, dan mengevaluasi.
Menurut KORAL, transparansi adalah pondasi awal yang menjadi penguat dan pengingat peran Pemerintah sebagai “abdi masyarakat”. Tentunya, sebagai seorang abdi, secara hakiki Pemerintah harus secara terus menerus berusaha melayani kepentingan masyarakat, memperlancar urusan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melayani, dan mengayomi masyarakat sebagai tugas utama mereka, sesuai amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bukan kemudian berkebalikan dengan sembunyi-sembunyi atau anti-kritik.
KORAL berharap PAM Jaya dapat dengan bijaksana dan amanah dalam menjalankan keputusan baru ini. Sehingga, hak untuk mendapatkan akses air bersih dapat dilakukan dengan optimal, inklusif, dan berbasis pada tonggak keadilan, transparansi, dan berkelanjutan.
***