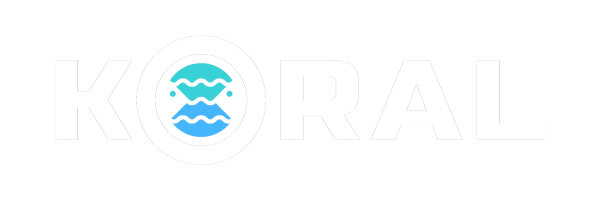Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menggelar United Nations Oceans Conference setelah lima tahun sebelumnya berlangsung di New York, Amerika Serikat, perhelatan level global ini digelar pada 27 Juni hingga 1 Juli 2022 di Lisbon, Portugal. Konferensi kali ini memiliki tema besar “Scaling up Ocean Action Based on Science and Innovation for the Implementation of Goal 14: Stocktaking, Partnerships and Solutions”. Peserta konferensi didorong untuk menghasilkan solusi inovatif berbasis sains yang sangat dibutuhkan dunia dengan tujuan untuk memulai babak baru aksi secara global. Solusi yang dimaksud mencakup tata kelola laut secara berkelanjutan melibatkan teknologi ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya laut secara inovatif. Kemudian solusi atas ancaman kesehatan, ekologi, dan ekonomi dari tingginya tingkat pengasaman, sampah dan polusi laut, aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan menyalahi aturan (IUUF), serta hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati.
Nyatanya, konferensi yang seharusnya berfokus pada keselamatan dan kelestarian keanekaragaman hayati ini justru mendorong perampasan ruang laut yang lebih besar dan berujung pada kepunahan perairan dan segenap biodiversitas didalamnya. Mengapa demikian? Dilansir dari WALHI, penyusunan tata kelola laut dunia didominasi oleh intervensi kepentingan korporasi multinasional yang hendak memonopoli dalam rangka ekstraksi sumber daya laut seluas-luasnya. Komersialisasi oleh korporasi transnasional ini juga mengindikasikan tidak adanya peran negara dalam pengawasan dan penindakan terhadap komersialisasi besar-besaran ini.
Carsten Pedersen, Peneliti Transnational Institute, menjelaskan ruang kemudi politik ekonomi kelautan global saat ini dikendalikan dengan kuat oleh 100 perusahaan transnasional (TNCs) yang menyumbang 60% dari modal yang terakumulasi dalam ekonomi laut, dimana 86% nya berasal dari perusahaan minyak dan gas lepas pantai dan industri perkapalan. Yang ia takutkan justru pembentukan Blue Action Fund oleh PBB sebesar 1 Miliar US Dollar, hanya akan menjadi “Blue-Washing” dan semakin melegitimasi lepasnya tanggung jawab korporasi terhadap hak-hak masyarakat korban yang terlanggar dan kerusakan lingkungan serta punahnya ekosistem laut yang ditimbulkan. Hal serupa pun disampaikan oleh Jesu Rathinam, dari National Fisherworkers Forum, India, menjelaskan bahwa pembahasan tata kelola laut di forum ini telah bergeser dari isu perlindungan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, ke arah ekstraksi ekonomi biru.
Pemerhati perikanan Indonesia pun serupa halnya. Indonesia yang menjadi bagian dalam konferensi internasional itu diwakilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyampaikan beberapa program dan kebijakan yang sudah atau akan diimplementasikan KKP, salah satunya adalah penangkapan ikan terukur dalam skema ekonomi biru. Nyatanya, kebijakan ini masih jauh dari kata ‘bijak’. Parid Ridwanudin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI dalam Siaran Pers WALHI, menegaskan bahwa tata kelola laut di Indonesia pun disusun untuk melayani kepentingan korporasi skala besar. Agenda strategi ekonomi biru Indonesia yang akan disampaikan oleh Pemerintah Indonesia di forum UN Global Ocean Conference jauh dari perlindungan masyarakat pesisir. Salah satunya yaitu kebijakan di bawah payung ekonomi biru yang sangat menguntungkan korporasi, yaitu penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang akan memberikan karpet merah kepada korporasi skala besar untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan.
Ia menambahkan, terkait dengan kawasan konservasi laut, WALHI menilai kawasan ini akan mudah diubah untuk kepentingan proyek-proyek ekstraktif seperti pertambangan dan juga diubah untuk kawasan neo-ekstraktif seperti proyek pariwisata skala besar. Hal ini telah disebut jelas dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Kelautan dan Perikanan.
Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, menjelaskan bahwa pertemuan UN Global Ocean Conference, merupakan satu dari berbagai pertemuan untuk mengundang negara maju untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berbasis korporasi. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang disusun seperti Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang menjadi legal affirmative untuk penguasaan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan modal dan bentuk peminggiran masyarakat lokal secara sah melalui regulasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia yaitu mendorong Marine Protected Area serta pengembangan kawasan konservasi, rehabilitasi pesisir dan laut, pengembangan SKPT di 7 pulau dan pengurangan sampah. Lima komitmen ini dapat dijadikan kedok sebagai pengusiran masyarakat pesisir dan pulau-pulau dari ruang hidup yang telah dikelolanya secara turun temurun,.
Nyatanya, Kebijakan penangkapan terukur sudah mendapatkan lampu hijau dari mayoritas anggota DPR untuk dijadikan Keputusan Menteri (KEPMEN). Alasan anggota DPR memberikan lampu hijau yaitu dikarenakan kebijakan ini paling tidak menggenjot pemasukan negara bukan pajak (PNBP), paling tidak 10% dari hasil keuntungan produksi perikanan yang hampir mencapai angka Rp 240 Triliun tersebut untuk masuk ke Negara. Sehingga alasan ini menjadi masuk akal bagi DPR. Padahal tidak semua anggota memahami betul apa yang menjadi kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan, apalagi efek atau pengaruhnya pada masyarakat pesisir maupun sumberdaya laut dan keberlanjutan. Hal ini dikarenakan pemahaman perspektif kontinental mereka dan masih lemahnya isu kelautan perikanan, yang sangat krusial untuk menghindari pengesahan kebijakan yang dapat berdampak sangat negatif.
Legislator asal Maluku, Saadiah Uluputty mengatakan bahwa ia tidak melihat grand design untuk memajukan kelautan perikanan oleh KKP. Ia mengungkapkan bahwa bahkan didalam Undang-Undang saja tidak ada kejelasan terkait definisi nelayan kecil. Selain itu, rezim yang digunakan di indonesia adalah rezim izin bukan kontrak sehingga ini melanggar aturan hukum tertinggi di indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Bukan hanya sektor KP saja, tapi mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan se-optimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
Meminjam slang word anak jaman sekarang, ‘flexing’ atau artinya memamerkan, pantaskah kemudian Indonesia atau halnya disini, KKP, flexing mengenai kebijakan ini di ranah dunia? Ataukah kenyataannya, kebijakan ekonomi sentris yang berkedok ekologi sentris sudah menjadi rahasia umum dan menjadi mata angin bagi pelayaran sektor kelautan dan perikanan dunia dengan destinasi kemerosotan akhlak, pelelangan wilayah perairan demi segepok uang, menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir, dan degradasi lingkungan berujung pada perubahan iklim?
******